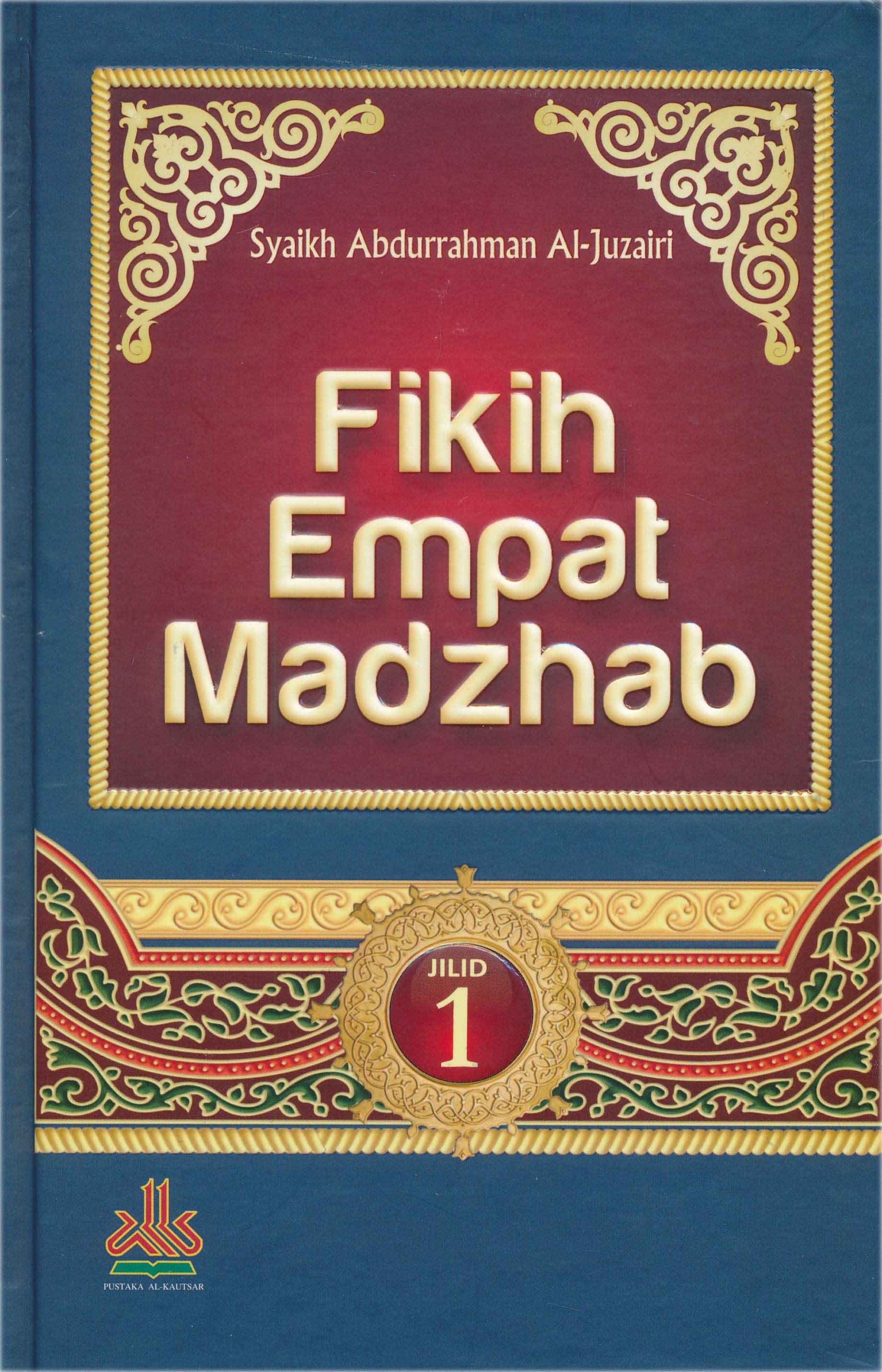Definisi
Yang dimaksud dengan thaharah dari sisi etimologi adalah bersuci. Bersuci dari kotoran dan najis, baik kotoran fisik maupun non fisik. Makna seperti ini sejalan dengan kandungan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Rasulullah Saw menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit, beliau bersabda,
‘Tidak apa-apa, Insya Allah suci.”7
Thuhur dalam kalimat ini bermakna fathur . Keduanya berarti murni atau suci, atau bersih dari dosa. Nabi pernah menyatakanbahwa sakit adalah pembersih dosa-dosa. Makna seperti ini mengarah pada kotoran non fisik, yaitu berupa dosa. Selain kotoran non fisik, thaharah atau bersuci juga meliputi bersuci dari najis. Najis secara etimologis berarti segala sesuatu yang kotor, baik itu yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. orang orang yang berdosa masuk kategori sebagai orang-orang yang najis. Akan tetapi najis dalam hal ini bukan yang kasat mata, melainkan najis maknawi (non materi). Makna ini dapat dirujuk dari firman Allah:
” Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.”(at-taubah : 28)
- HR. Al-Bukhari / Ktab Al-Mardtu (75) / Bab MnYuqaluli Al-MaidhwaMaYujib Q.4)/hadits nomor 5662, dan di beberapa tempat lain. Hadits ini juga diriwayatkan Ath-Thabarani dalamAl-Knbir (11951), Al-Baihaqi dalamsunanrtya (382), Al-BaghawidalamsyarhAs- Sunn ah (1.472), dan Ibnu Hibban (2959).
Sementara definisi thaharah dan najis dalam terminologi ulama fikih dapat dilihat secara lebih detil dari masing-masing madzhab.
Madzhab Hanafi: Thaharah secara syar’i adalah bersih dari hadats maupun kotoran dan najis. Dalam pandangan madzhab Hanafi, thaharah atau bersuci dapat berupa perbuatan seseorang membersihkan sesuatu yang najis atau kotor, sebagaimana thaharah dapat pula berupa bersihnya sesuatu yang kotor atau najis dengan sendirinya. Misalnya, karena benda tersebut tersiram air bersih tanpa ada orang yang menyirarnnya. Sementara hadats meliputi hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil dapat berupa keluarnya angin melalui lubang dubur, air kencing, dan semacarmya. Hadats kecil dapat dihapus dengan berwudhu. Adapun hadats besar adalah berupa keadaan junub yang dapat dihilangkan dengan cara melakukan mandi wajib. Madzhab Hanafi mengartikan hadats sebagai sesuatu yang bersifat
syar’i yang dapat dihapus dengan cara membersihkan sebagian anggota badan maupun seluruh tubuh. Dengan demikian maka thaharah tersebut dapat menghapus hadats. Sebagian dari kalangan Hanafi mengartikan hadats sebagai najis maknawi (non fisik). Dalam hal ini, seolah-olah pembuat syariat menghukumi hadats sebagai najis yang menghalangi sahnya shalat, sebagaimana halnya najis fisik yang juga menghalangi sahnya shalat. Adapun kotoran dalam istilah syar’i adalah semua benda yang kotor yang oleh syariat diperintahkan untuk dibersihkan (disucikan). Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa najis adalah lawan dari suci. Dan
najis sendiri mgliputi dua hal, berupa hadats dan kotoran, baik itu kotoran yang bersifat kasat mata seperti darah, air kencing, kotoran air besar dan sejenisnya, maupun kotoran yang bersifat non fisik seperti dosa. Adapun para ulama sejatinya telah membatasi makna hadats sebagai bagian dari hal yang bersifat maknawi (bukan benda). Bahwa hadats adalah semacam sifat maknawi yang oleh syariat dihukumi sebagai hal yang melekat pada seluruh tubuh manakala seseorang tengah dalam keadaan junub, atau hanya sebagian anggota badan berupa area wudhu, manakala seseorang berhadats kecil. Sedangkan kotoran dalam pandangan para ulama adalah terbatas pada perkara-perkara kebendaan yang oleh syariat dihukumi
sebagai benda yang kotor, seperti darah dan sebagainya. Mungkin ada orang berpandangan bahwa pengertian atau definisi seperti ini tidak mencakup wudhu yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak berhadats, dengan niat untuk bertaqarrub kepada Allah. Jadi wudhu yang kedua tidak menghilangkan hadats dan tidak pula mengangkat kotoran, sebab orang tersebut manakala berwudhu masih
dalam keadaan suci dari hadats. Untuk pandangan ini maka kami katakan bahwa meskipun tidak menghilangkan hadats, wudhu yang dilakukan untuk bertaqarub kepada Allah saat seseorang masih dalam keadaan suci adalah wudhu yang juga
tetap menghapus dosa-dosa kecil. Dan sebagaimana jamak diketahui bahwa
dosa-dosa kecil termasuk bagian dari kotoran atau najis yang bersifat maknawi. Perlu diketahui bahwa secara etimologis kotoran mencakup perkara-perkara yang bersifat maknawi, meskipun dalam definisi di atas ada batasan makna kotoran yang mencakup perkara-perkara yang bersifat kebendaan. Namun para ulama juga menegaskan bahwa menghilangkan kotoran-kotoran yang bersifat maknawi adalah thaharah. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa wudhu yang dilakukan saat seseorang masih dalam keadaan suci masuk dalam kategori pengertian thaharah. Ada lagi yang mengajukan sanggahan atas pengertian di atas, bahwa
dengan definisi tersebut maka tidak ada artinya angin (kentut) sebagai perkara yang membatalkan wudhu, demikian pula berhubungan seksual di luar nikah tanpa keluar airmani. Tidak ada artinya pula airmani sebagai hal yang menyebabkan mandi wajib. Pasalnya, angin kentut atau semisalnya bukan termasuk najis fisik, dan mani itu sendiri adalah suci. Kalaupun ada yang menganggap air mani adalah najis, maka kadar kenajisan air mani tidak melebihi najisnya urin ataupun tinja. Dengan begitu maka logikanya thaharah hanya perlu dilakukan sebatas pada menyiram tempat di mana kotoran itu berada.
Untuk sanggahan seperti ini, kami katakan bahwa orang yang mengatakan kata-kata ini lalai akan makna ibadah, dan lalai akan makna tatacara ibadah. Perlu dicatat bahwa tujuan ibadah sesungguhnya tidak lain adalah tunduk dan patuh kepada Allah, mulai dari hati hingga seluruh indera dalam bentuk sebagaimana digariskan oleh Allah. Oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang dalam melakukan ibadah keluar dari batas lingkaran yang telah digariskan oleh Allah atas hamba-hambaNya. Demikian pula tidak ada manfaat sedikit pun untuk kepentingan manusia mempermasalahkan tata cara serta bentuk ibadah kecuali manakala ia berada pada kondisi sakit atau kelelahan. Dalam kondisi seperti ini, ia memiliki hak untuk menuntut beban syariat sebatas yang ia sanggup.Adapun tata cara dan bentuk-bentuk ibadah di luar kondisi tersebut, sudah seharusnya semata-mata mengikuti
kehendak Allah yang kita sembah. Masalah ini sangat jelas tanpa keraguan apa pun bahkan sampai pada hal-hal yang berlaku di kalangan umat umat manusia dalam memuliakan orang-orang tertentu. Misalnya, para raja atau pemimpin tidak ditanya akan alasan-alasan di balik berbagai ketentuan atau tata cara yang telah diterima dan dipraktikkan oleh orang-orang, sepanjang hal itu tidak memberatkan. Manakala pembuat syariat ini mengatakan, “janganlah kalian kerjakan shalat dalam keadaan berhadats.” Apakah itu hadats kecil ataupun hadats besar, kewajiban kita hanyalah menuruti dan menjalankan perintah tersebut tanpa perlu menanyakan kenapa. Jika tidak demikian kita memahaminya, sudah barang tentu boleh jadi kita akan juga
menanyakan untuk apa kita shalat.
Pada dasarnya dua hal tersebut tidak berbeda secara substansi, bahwa larangan mengerjakan shalat saat berhadats dan atau melakukan shalat tanpa bertanya kenapa atau untuk apa adalah bentuk dari ibadah dan tata cara beribadah itu sendiri. Allah telah menetapkan larangan shalat dalam keadaan hadats mestinya dipahami dalam kerangka tunduk dan patuh semata-mata pada perintah dan larangan Allah tanpa perlu mengajukan pertanyaan mengapa dan kenapa. Yang dibenarkan untuk kita ajukan pertanyaan adalah bagaimana jika kita tidak sanggup berwudhu, atau
melakukan mandi wajib, atau bahkan tidak mampu melakukan shalat.
Pertanyaannya lalu apa yang mesti kita lakukan? Untuk itu Allah telah menetapkan syariat bagi yang berhalangan atau tidak sanggup berwudhu dan mandi wajib, berupa tayamum. Sementara untuk yang tidak sanggup mengerjakan shalat, maka Allah membolehkan mengerjakan shalat dengan duduk, atau berbaring atau dalam keadaan yang sanggup dilaksanakan oleh seorang hamba. Yang pantas untuk kita tanyakan dan kita diskusikan adalah hal-hal yang menyangkut hak-hak kita. Adapun yang secara khusus menjadi hak Allah maka cukup kita menjalankan tanpa perlu menanyakan kenapa apalagi mendiskusikannya. Hal ini berbeda dengan persoalan persoalan muamalat atau persoalan-persoalan rumah tangga.
Kedua aspek ini sangat bersinggungan dengan kehidupan kita, sehingga kita berhak mengetahui segala hikmah di balik setiap ketetapan. Demikian pula kita dapat mendiskusikan persoalan-persoalan furu’iyah (cabang). Pendapat ini masuk akal, meskipun beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa setiap masalah syariat memiliki hikmah yang logis dan rasional serta rahasia yang jelas, yang hanya dimengerti oleh mereka yang mengerti dan tidak dapat ditangkap oleh mereka yang tidak sanggup, baik itu dalam masalah ibadah maupun muamalah. Untuk yang pertama telah terjawab, bahwa angin yang keluar dari lubang dubur (kentut) adalah
kotor secara fisik. Tidak diragukan bahwa meskipun angin kentut tidak dapat ditangkap oleh penginderaan mata, akan tetapi dapat ditangkap oleh indera penciuman. Sementara mereka yang mengatakan bahwa kentut tidak membatalkan wudhu, dan bahwa urine serta tinja hanya wajib dibasuh pada tempatnya saja, sudah barang tentu logika mereka akan mengadopsi pandangan yang menyatakan bahwa seseorang hanya cukup satu kali saja sepanjang hidup untuk berwudhu, dan bahwa tidur bukanlah termasuk membatalkan wudhu, demikian pula dengan kentut. Mereka tentu juga sejalan untuk menyatakan bahwa urine dan tinja merupakan najis yang bersifat lokal yang hanya terbatas pada tempatnya semata’ Pandangan semacam ini jelas-jelas tidak dapat diterima. Pasalnya Allah mensyariatkan wudhu untuk beberapa manfaat yang nyata, baik untuk hal-hal yang dapat diindera atau dapat dilihat maupun untuk hal-hal yang tidak kasat mata dan tidak dapat diindera. Yang dapat diindera misalnya untuk menjaga kebersihan anggota badanyang rawan danmudah terkena kotoran seperti mulut dan hidung. Sementara manfaat untuk hal-hal yang tidak dapat diindera adalah bdhwa melakukan wudhu merupakan bentuk
menaati perintah Allah dengan sepenuh hati hingga seseorang dapat merasakan kebesaran Allah selama-lamanya. Dengan demikian orang yang gemar berwudhu akan dapat menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat. Tentu saja hal ini menjadi kebaikan dan manfaat bagi manusia baik di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh karena itu, pandangan yang mengatakan bahwa wudhu cukup satu kali seumur hidup karena buang air maupun kentut tidak dapat membatalkan wudhu, tentu saja akan menghilangkan manfaat dan faedah dari disyariatkannya wudhu. Untuk sanggahan yang kedua, maka jawaban kami bahwa menganalogikan urine dan tinja dengan air mani bukan analogi yang tepat. Sebaliknya merupakan analogi yang jelas-jelas tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa air mani keluar dari semua bagian dari tubuh. Hal ini sudah menjadi kesepakatan umum. Selain itu, keluarnya air mani juga memerlukan sejumlah usaha tertentu yang manakala selepas keluarnya air mani tubuh menjadi lemah. Dengan begitu maka jelaslah bahwa mandi wajib yang disyariatkan setelah seseorang berjunub dapat memulihkan kebugaran dan
mengembalikan beberapa hal yang hilang akibat mengeluarkan air mani.
Di samping manJaat seperti ini sesungguhnya diwajibkannya melakukan mandi besar setelah seseorang berjunub menggambarkan betapa indahnya syariat lslam. Seorang lelaki tentu tidak bisa lepas dari kaum hawa sehingga membersihkan tubuh dari kotoran menjadi kebutuhan wajib. Jika tidak, bisa saja seseorang akan bermalas-malas unfuk mandi dan membersihkan diri sehingga kotoran menumpuk di tubuhnya. Dengan begitu akan banyak orang yang terganggu oleh aroma tubuhnya yang tidak sedap. Lantas bagaimana air mani dianalogikan dengan urine dan tinja, padahal kedua hal terakhir merupakan hal yang biasa terjadi berulang-ulang tanpa
memerlukan usaha tertentu. Atas dasar itu maka qiyasf analogi tersebut tidak dapat diterima dari aspek rulna pun. Namun demikian, yang perlu digaris bawahi bahwa ibadah harus dilakukan tulus semata-mata sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah tanpa mempedulikan apa pun manfaat yang dapat diperoleh di dunia ini, meskipun sudah pasti manfaat tersebut ada.
Madzhab Maliki: Thaharah adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya, serta tempat di mana shalat tersebut dikerjakan. Makna dari sifat maknawi adalah bahwa thaharah merupakan keadaan (kondisi) yang ditetapkan Allah sebagai syarat sahnya shalat dan atau semacamnya. Manakala sifat tersebut terdapat pada tempat yang akan digunakan untuk shalat, maka seseorang boleh melaksanakan shalat di tempat tersebut. Begitu pula ketika sifat tersebut ada pada pakaian yang akan digunakan untuk shalat, maka orang tersebut boleh mengenakan pakaianya untuk melakukan shalat. Sifat seperti ini merupakan perkara maknawi, bukan perkara yang dapat diindera atau dilihat. Sebagai lawan thaharah dalam makna seperti ini adalah najis dan hadats. Najis sendiri merupakan sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan shalat, baik dengan pakaian ataupun tempat di mana shalat tersebut dikerjakan. Sementara hadats adalah sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan shalat. Ringkasnya, najis
merupakan sifat maknawi yang ada kalanya melekat pada pakaian sehingga terlarang menggunakannya untuk shalat. Ada kalanya melekat pada tempat di mana shalat tersebut dikerjakan, sehingga terlarang mengerjakannya di tempat tersebut. Dan ada kalanya juga melekat pada diri seseorang yang disebut hadats. Karena itu ia terlarang melakukan shalat dalam keadaan berhadats. Intinya, bahwa hadats adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah, yang biasa dikenal sebagai perkara yang membatalkan wudhu, sedangkan najis biasa dikenal sebagai kotoran-kotoran tertentu seperti urine, tinja, darah, dan yang lainnya.
Madzhab Asy-Syafi’i: Thaharah secara syar’i mencakup dua makna’
Pertama; Melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan shalat. Sesuatu di sini berupa wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan kotoran (najis), atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi, misalnya melakukan tayamum, mandi sunnah, ataupun berwudhu saat masih dalam keadaan suci. Penjelasan dari definisi ini bahwa membasuhkan air pada wajah
dan anggota badan lain dengan niat berwudhu dapat dikatakan sebagai thaharah. Jadi thaharah merupakan tindakan seseorang. Sedangkan maksud dari’atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi’ mengandung arti bahwa perbuatan tersebut iuga merupakan thaharah. Artinya, thaharah merupakan sebutan atau nama dari perbuatan seseorang. Akan tetapi thaharah seperti ini tidak berdampak pada bolehnya melakukan shalat. Pasalnya, dibolehkannya shalat adalah karena telah terpenuhinya wudhu yang dilakukan saat seseorang berhadats, atau yang disebut wudhu pertama. Sedangkanwudhu yang dilakukan saat seseorang sudah dalam keadaan suci atau yang biasa disebut wudhu setelah wudhu tidak berdampak pada boleh tidaknya melakukan shalat. Demikian pula dengan mandi sunnah, sebab yang menghalangi dapat dilaksanakannya shalat adalah keadaan junub, di mana cara mensucikannya adalah dengan melakukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Oleh karena itu, hal ini mesti masuk dalam definisi thaharah supaya hal-hal yang menjadi bagian dari thaharah dalam arti seperti ini tidak tereliminir. Kedua; Thaharah adalah menghilangkan hadats, atau membersihkan kotoran, atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal itu. Misalnya, tayamum, mandi sunnah, dan semacamnya. Di sini, thaharah diartikan sebagai semacam sifat maknawi yang berdampak pada,munculnya suatu perbuatan. jadi hadats dapat dihilangkan dengan wudhu atau mandi iika itu adalah hadats besar, di mana arti menghilangkan atau dihilangkan
didasarkan pada perbuatan seseorang. Sedangkan najis atau kotoran dapat dihilangkan dengan cara menyiramnya. Ini adalah makna thaharah yang dimaksud. Adapun makna thaharah yang pertama sebagai suatu perbuatan tidak lain merupakan makna kiasan.
Madzhab Hambali: Thaharah secara syar’i adalah menghilangkan hadats atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Maksud dari menghilangkan hadats adalah menghilangkan segala sifat yang menghalangi dapat dilaksanakannya shalat atau sejenisnya.
Sebab, hadats merupakan semacam sifat maknawi yang melekat pada seluruh anggota badan ataupunsebagian. jadi thaharah berarti mengangkat sifat tersebut. Sementara yang dimaksud dengan’atau semacarmya’ dalam pengertian thaharah adalah tindakan yang mengandung makna seperti menghilangkan hadats. Misalnya, memandikan mayat, meskipun hal itu tidak mengangkat hadats, akan tetapi itu merupakan perkara ibadah.
Contoh lain adalah melakukan wudhu ketika masih memiliki wudhu, hal mana juga bukan untuk menghilangkan hadats. Semua itu masuk dalam pengertian seperti menghilangkan hadats meskipun tidak menghilangkan hadats. Sedangkan yang dimaksud dengan’membersihkan najis’ dalam pengertian di atas mencakup baik perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang seperti menyiramkan air di tempat yang terkena najis, ataupun najis yang hilang dengan sendirinya, seperti berubahnya khamer menjadi cuka. Sedangkan maksud dari menghilangkan hukumnya’ dalam
pengertian thaharah di sini adalah menghilangkan hukum hadats maupun najis atau apa saja yang semakna dengan itu. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan debu (tanah), yaitu tayamum dari hadats maupun kotoran. Jadi, tayamum dapat menghilangkan hukum hadats maupun hukum najis, yang mana dapat menghalangi pelaksanaan shalat.
bersambung ke : …………….