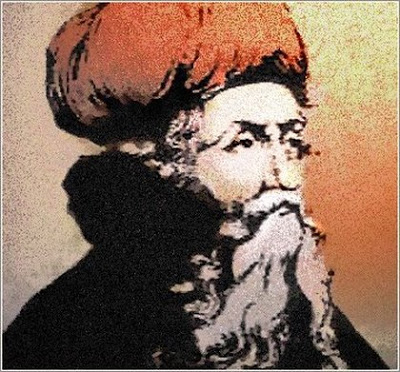Oleh : Kautsar Azhari Noer1
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
E-mail: kautsar_noer@yahoo.com
Abstrak
Artikel ini adalah sebuah usaha untuk menganalisis pandangan Ibn ‘Arabi tentang takwil al-Qur’an. Syekh Sufi dari Andalusia ini menolak takwil yang dikendalikan oleh penalaran, pemikiran, refl eksi dan hawa nafsu karena takwil jenis ini melenceng dari apa yang dimaksud oleh Allah dengan kata-kata-Nya yang dikadung oleh Kitab-Nya. Tetapi ia menerima takwil yang dibimbing oleh Allah melalui penyingkapan intuitif (kasyf), yaitu takwil yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang diberi-Nya keberhasilan dalam memahami apa yang Dia maksud dengan kata-kata yang dikandung oleh Kitab-Nya. Takwil yang didukung oleh Ibn ‘Arabi ini tetap mempertahankan kesesuaian antara arti lahiriah dan arti batiniah.
Kata-kata Kunci: Tasawuf teosofi , ta’wīl, ayat-ayat muhkamāt, ayat-ayat
mutasyābihāt, persesuaian, keserupaan, pemberian (wahb).
Pendahuluan
Para ulama yang menolak tasawuf dan para ulama yang mengaku sebagai penganut tasawuf Sunni, yang menolak apa yang mereka sebut tasawuf falsafi , menilai bahwa tafsir esoterik Sufi atas al-Qur’an adalah tafsir yang sesat dan menyesatkan, karena tafsir jenis ini tidak didasarkan pada kaidah-kaidah tafsir yang benar. Mereka menganggap bahwa para Sufi telah menafsirkan al-Qur’an sesuai dengan keinginan mereka untuk mendukung ajaran-ajaran tasawuf yang telah bercampur dengan ajaran-ajaran fi lsafat dari luar Islam.
Mereka menuduh bahwa para Sufi telah menjadikan al-Qur’an tunduk pada pokok-pokok pemikiran tasawuf yang menyimpang dari petunjuk al-Qur’an. Dalam pandangan mereka, takwil yang dilakukan para Sufi adalah takwil liar yang keluar jauh dari maksud yang dikandung al-Qur’an. Para ulama yang membela tasawuf teosofi atau ‘irfan pasti menolak kecaman terhadap tafsir Sufi . Mereka memandang bahwa tafsir Sufi memiliki kelebihan yang tidak dimilki oleh tafsir-tafsir lain. Kelebihan itu adalah kemampuannya untuk mengungkapkan bukan hanya makna lahiriah ayat ayat al-Qur’an tetapi juga makna batiniah karena setiap ayat al-Qur’an
mengandung makna lahiriah dan makna batiniah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad saw, “Dalam setiap ayat ada makna lahir dan ada makna batin.” Makna batin sama sekali tidak menghilangkan makna lahir. Karena al-Qur’an dalam bentuk aktual yang diwahyukan adalah pengejawantahan rahmat dan petunjuk ilahi, Ibn ’Arabi memperlihatkan penghormatan besar pada teks harfiah. Bentuk linguistik teks harus didahulukan daripada semua yang lain. Beberapa sarjana Barat melukiskan Ibn ‘Arabi sebagai seorang pengguna utama takwil (ta’wīl, tafsir esoterik), yang menjadikan makna harfi ah teks sebagai pintu untuk memasuki alam gaib. Orang bisa setuju dengan pernyataan ini, sejauh dipahami bahwa tidak ada penafsir Muslim yang memiliki perhatian seperti Syekh Sufi ini untuk menangkap arti harfi ah al-Qur’an. Ibn ’Arabi tidak pernah menolak makna harfi ah dan lahiriah, tetapi ia sering menambahkan kepada arti harfiah suatu interpretasi yang didasarkan pada penyingkapan intuitif (kasyf) yang melampaui keterbatasan-keterbatasan kognitif kebanyakan manusia. Ia sering memberitahukan kepada kita bahwa Allah mungkin menyingkapkan makna makna teks kepada para arif (ahli makrifah) yang tidak pernah ditangkap oleh orang-orang lain, dan penyingkapan-penyingkapan ini bisa dipercayai sejauh tidak menyangkal atau bertentangan dengan makna harfiah.2. Orang-orang yang berkenalan dengan Ibn ‘Arabi melalui karya karya Henry Corbin, seorang sarjana Studi Keislaman asal Perancis, telah memperoleh pengetahuan bahwa takwil adalah salah satu dasar pemikiran Syekh ini. Orang tidak dapat menolak Corbin karena mengatakan bahwa Ibn ‘Arabi menakwilkan ayat-ayat al-Qur’an, tetapi orang dapat menolak pemilihannya pada kata ta’wīl untuk menyebut proses (tafsir esoterik) itu, karena Ibn ‘Arabi tidak menggunakan istilah ini dalam arti positif sebagaimana yang dipahami Corbin.3 Kesan bahwa takwil adalah sentral dalam sistem Ibn ‘Arabi semakin kuat ketika orang mengetahui bahwa Nashr Hamid Abu Abu Zayd menulis sebuah karya yang berjudul Falsafat al-Ta’wīl: Dirāsah fī Ta’wīl al-Qur’ān ‘inda Muhyi al-Dīn Ibn ‘Arabi.4 Kesan ini bertolak belakang dengan kritik Ibn ‘Arabi terhadap takwil yang dilakukan oleh para ulama. Maka timbul pertanyaan: bagaimana sebenarnya sikap Ibn ‘Arabi terhadap penggunaan takwil? Apakah ia menolak atau menerima penggunaan takwil?
Takwil: Dibolehkan atau Dilarang?
Pada kesempatan ini kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan
takwil. Takwil “pada asalnya: pengembalian (fī al-ashl: al-tarjī‘),”5 yaitu
menggiring kembali atau membawa kembali sesuatu kepada asalnya.6 Maka
orang yang mempraktikkan takwil adalah “orang yang membelokkan apa
yang dinyatakan dari penampakan luarnya (aspek eksoterik atau lahirnya)
dan mengembalikannya kepada kebenarannya, hakikatnya.” Inilah takwil
sebagai tafsir spiritual batiniah, sebuah tafsir yang simbolik, esoterik, dan seterusnya.7 Takwil dalam syarak adalah “memalingkan lafaz dari makna lahirnya kepada makna yang dikandungnya bila makna yang terkandung itu dilihatnya sesuai dengan al-Kitab dan al-Sunnah.”8. Ibn Rusyd mengatakan, “Takwil adalah mengeluarkan makna lafaz dari makna hakiki kepada makna majazi (kiasan), tanpa melanggar kebiasaan bahasa Arab.”9. Karena itu, ada perbedaan antara takwil dan tafsir, karena tafsir adalah syarah makna lafaz-lafaz dan penjelasannya, sedangkan takwil adalah mengarahkan lafaz nas-nas kepada makna yang bukan ditunjukkan oleh zahirnya.”10 Ibn ‘Arabi mengatakan, “Bila ditemukan ayat al-Qur’an atau khabar (hadis) dengan lafaz apapun dari bahasa, maka prinsip [yang dipegang] adalah diambilnya [makna] dengan apa adanya dalam bahasa Arab,”11 yaitu tanpa takwil, tetapi kadang kala takwil menjadi perlu.12 Telah ditemukan dalam “al-Qur’an dan al-Sunnah di antara deskripsi al-Haqq (Tuhan) tentang diri-Nya yang tidak diterima oleh akal kecuali dengan takwil yang benar.”13
Di antara ayat-ayat al-Qur’an ada yang tidak jelas maknanya, yang tidak
diterima oleh akal kecuali oleh orang yang mempunyai kemampuan
berpikir yang sehat. Di antara ayat-ayat al-Qur’an ada maknanya yang
terbuka bagi ulū al-albāb, dan mereka adalah orang-orang berakal (al-
‘uqalā’) dan orang-orang yang memandang (al-nāzhirūn) ke dalam isi,
bukan kulit. Mereka adalah orang-orang yang melihat makna-makna,
meskipun al-albāb dan al-nuhā adalah akal-akal (al-‘uqūl). Allah tidak
memandang cukup lafaz “akal” (al-‘aql) sehingga Dia menyebut ayat ayat
al-Qur’an bagi ulū al-albāb. Tidak setiap orang berakal melihat ke dalam isi akar-akar dan batin-batinnya karena tidak diragukan ahli zahir (ahl al-zhāhir) memiliki akal, tetapi mereka bukan ulū al-albāb. Tidak diragukan bahwa para pelaku maksiat mempunyai akal, tetapi mereka bukan ulū al-albāb. Sifat-sifat mereka berbeda. Maka setiap sifat memberikan jenis ilmu, yang tidak akan datang kecuali bagi orang yang keadaannya adalah sifat itu. Allah tidak menyebutnya sia-sia.14
Tidak salah bila dikatakan bahwa Ibn ‘Arabi, seperti diungkapkan di atas, adalah seorang pengguna utama takwil yang menjadikan makna harfiah teks sebagai pintu untuk memasuki alam gaib, sejauh itu dipahami bahwa tidak ada penafsir Muslim yang perhatiannya sebesar Syekh ini untuk memelihara arti harfi ah Kitab ini [al-Qur’an]. Ia tetap mempertahankan arti harfi ah ayat-ayat al-Qur’an ketika memasuki arti metaforisnya. Ia tetap memelihara arti lahiriah ayat-ayat al-Qur’an ketika memasuki arti batiniahnya. Dengan kata lain, bagi Syekh ini ayat-ayat al-Qur’an memiliki arti lahiriah dan arti batiniah sekaligus.
Ayat yang sering dikutip untuk membicarakan masalah takwil adalah firman Allah sebagai berikut, yang dibaca dengan dua cara. Pertama, “Dialah yang telah menurunkan Kitab (al-Qur’an) kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamāt. Itulah Ibu Kitab. Dan yang lain adalah [ayat ayat] mutasyābihāt. Adapun tentang orang-orang yang dalam kalbunya penyimpangan, mereka mengikuti bagian mutasyābihāt untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya; padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berakar kukuh dalam ilmu; mereka berkata, ‘Kami beriman kepadanya (al-Qur’an); semuanya dari Tuhan kami.’ Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali ulū al-albāb” (Q 3:7).
Kedua, sama dengan cara membaca pertama kecuali bagian “padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang berakar kukuh dalam ilmu berkata, “Kami beriman kepadanya (al-Qur’an)”(3:7).
Cara pertama menyambungkan “Allah” dan “orang-orang yang berakar kukuh dalam ilmu,” yang membuat satu kalimat yang menyatu, sedangkan cara kedua memisahkan “Allah” dari “orang-orang yang berakar kukuh dalam ilmu” untuk berhenti penuh, yang membuat dua kalimat yang terpisah.
Cara membaca pertama diikuti oleh para ulama yang mempertahankan takwil sebagai cara yang sah untuk memperoleh ilmu, sedangkan cara membaca kedua diikuti oleh para ulama yang menolak takwil untuk memperoleh ilmu. Ibn ‘Arabi mengikuti cara membaca pertama dengan tetap memegang teguh implikasi bagian ayat “Kami beriman kepadanya (al-Qur’an).” Takwil adalah kunci-kunci kegaiban (mafātīh al-ghayb), yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, dan setiap apa yang diketahui oleh Allah bergantung kepada-Nya, yang diketahui hanya oleh orang yang Dia beritahu dan perlihatkan kepadanya. Orang-orang yang berakar kukuh dalam ilmu diberitahu oleh Allah takwil atas kehendak-Nya.15 Tampaknya orang-orang seperti inilah yang, menurut Ibn ‘Arabi, orang-orang yang diajari oleh Allah al-Qur’an, yang sekaligus berakhlak dengan al-Qur’an, yang tidak lain adalah akhlak Allah. Orang-orang seperti inilah yang dia sebut “orang-orang al-Qur’an” (ahl al-qur’ān) atau “orang-orang Allah” (ahlu-Llāh). Mereka inilah orang-orang yang mengambil pelajaran dan mereka inilah yang disebut ulū al-albāb, yang berarti “orang-orang yang menangkap isi akal, bukan kulitnya (al-ākhidzūna bi-lubb al-‘aql lā biqisyri-
hi).”16 “Mereka adalah para penyelam yang memindahkan keluar isi ilmu-ilmu kepada penyaksian hakiki, setelah isi itu ditutup oleh kulit luar yang disertai oleh perlindungannya.”17.
Dua Jenis Ilmu: Pemberian dan Perolehan
Ayat lain yang terkait dengan takwil, yang bersama ayat di atas (Q 3:7) diulas oleh Ibn ‘Arabi, adalah firman Allah:
“Sekiranya mereka menegakkan (melaksanakan secara sungguh-sungguh) Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, nicaya mereka akan makan apa yang dari atas mereka dan apa yang dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada umat yang moderat, tetapi kebanyakan mereka buruk apa yang mereka kerjakan” (Q 5:66).
Dengan merujuk pada ayat ini, Ibn ‘Arabi membagi ilmu-ilmu menjadi dua jenis: “pemberian”(mawhūbah) dan “perolehan” (muktasabah).18 Jenis pertama, “pemberian,” ditunjukkan oleh kata-kata Allah, “mereka akan makan apa yang dari atas mereka” (laakalū min fawqi-him) (Q 5:66).
Ilmu-ilmu jenis ini adalah hasil takwa, sebagaimana Allah berfirman :
“Bertakwalah kepada Allah, dan Dia akan mengajarimu” (Q 2: 282). “Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan bagimu pembedaan (furqān)” (Q 8:29). “Yang Maha Pengasih mengajarkan al-Qur’an” (Q 55:1-2).
Orang-orang yang diberi ilmu-ilmu jenis pertama ini adalah orang-orang yang menegakkan Kitab Allah dan “apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka” (Q 5:66). Mereka adalah “orang-orang yang bersegera dalam kebajikan-kebajikan dan berlomba-lomba untuknya” (Q 23:61). Sebagian di antara mereka berlomba-lomba untuk kebajikan-kebajikan, dan sebagian lain menegakkan Kitab dari tempat tidurnya, karena takwil dari pihak ulama telah membaringkan Kitab itu setelah ia tegak. Maka orang yang diberi keberhasilan oleh Allah datang dan menegakkan Kitab dari tempat tidurnya. Dengan kata lain, orang itu membersihkan Kitab dari takwilnya dan dari pengerahan segala tenaganya dalam berpikir. Karena itu, ia melakukan ibadah kepada Tuhannya dan meminta-Nya untuk memberinya
keberhasilan dalam memahami apa yang Tuhan maksud dengan kata-kata yang dikandung oleh Kitab dan informasi, yaitu makna-makna yang bersih dari dasar derivasi bahasa. Maka Allah memberi orang-orang seperti itu ilmu yang tidak bercampur atau ilmu yang murni (al-‘ilm ghayr masyūb). Mereka disebut “orang-orang yang berakar kukuh dalam ilmu” (al-rāsikhūna fī al-‘ilm) dalam al-Qur’an, sebagaimana Allah berfi rman, “Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-rang yang berakar kukuh dalam ilmu” (Q 3:7). Tuhan mengajari mereka apa yang menjadi tempat kembali (mā ya’ūlu ilayhi) lafaz diwahyukan yang tertulis, yaitu makna makna yang disimpan oleh Tuhan di dalamnya. Mereka tidak menggunakan pemikiran (fikr), karena pemikiran tidak terpilihara dari kesalahan bagi siapa pun. Itulah sebabnya mengapa Allah mengatakan, “dan orang-orang yang
berakar kukuh dalam ilmu; mereka berkata, … Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami melenceng” (Q 3: 7-8). Ini berarti bahwa mereka memohon kepada Allah agar hati mereka dijauhkan dari pemikiran tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah setelah Dia menunjuki mereka ilmu yang telah diturunkan kepada mereka, sebagaimana Dia katakan, “setelah Engkau menunjuki kami” (Q 3:8). Lanjutan permohonan mereka adalah “dan berilah kami rahmah dari Engkau; sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi” (Q 3:8). Mereka memohon kepada Tuhan dari segi pemberian (wahb), bukan dari segi perolehan (kasb).
Jenis kedua, “perolehan,” diisyaratkan oleh kata-kata Allah, “apa yang dari bawah kaki mereka” (min tahti arjuli-him) (Q 5:66), yang menunjukkan kerja keras (kadd) dan ijtihad mereka. Mereka adalah orang-orang yang menakwilkan Kitab Allah dan tidak menegakkannya dengan amal. Mereka tidak menaati adab dalam mengambil Kitab Allah. Orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu perolehan, yang disebut “orang-orang perolehan” (ahl al-kasb), menurut Ibn ‘Arabi, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok moderat. Orang-orang yang termasuk dalam
kelompok ini disebut “orang-orang moderasi” (ahl al-iqtishād). Kelompok inilah yang dimaksud dalam kata-kata Tuhan, “Di antara mereka ada umat moderat” (min-hum ummah muqtashidah) (Q 5:66). Jumlah kelompok ini sedikit. Mereka adalah orang-orang yang mendekat pada kebenaran, dan mereka boleh jadi mencapai kebenaran dengan apa yang mereka takwilkan berdasar atas kesesuaian (muwāfaqah), bukan berdasar atas kepastian (qath‘), karena mereka tidak mengetahui dengan pasti apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam apa yang Dia diturunkan. Apa yang diturunkan itu hanya bisa diketahui dengan pemberian (wahb), yang merupakan pemberitaan
ilahi (ikhbār ilāhī) oleh Tuhan yang ditujukan kepada kalbu hamba dalam rahasia antara keduanya (Tuhan dan hamba).
Kelompok kedua adalah orang-orang yang tenggelam jauh dalam takwil yang tidak menyisakan persesuaian (munāsabah) antara kata-kata yang diwahyukan dan makna. Jumlah mereka adalah yang paling banyak di antara “orang-orang perolehan.” Atau mereka menetapkan dengan jalan keserupaan (tasybīh) dan tidak mengembalikan ilmu tentang itu kepada Allah. Inilah orang-orang yang disinggung dalam ayat al-Qur’an, “tetapi kebanyakan mereka adalah buruk apa yang mereka kerjakan” (Q 5:66). Ibn ‘Arabi menilai bahwa takwil mendatangkan akibat buruk bagi iman. Perhatikan kata-katanya yang dikutip berikut:
Ketahuilah bahwa derajat-derajat kedekatan pada Tuhan diketahui dengan ilmu pemberi syariat, yang bertindak sebagai juru bicara Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk beriman pada ayat-ayat muhkam dan mutasyābih al-Qur’an. Marilah kita menerima semua yang dibawa oleh Nabi, karena jika kita menakwilkan sesuatu dari itu dengan mengatakan bahwa ini adalah apa yang dimaksud oleh Pembicara dengan kata-kata- Nya, maka derajat iman hilang dari kita. Argumen kita akan menguasai berita (khabar), yang dengan demikian menjadikan hukum iman sia-sia.
Ketika itu terjadi, maka orang mukmin tampil dengan membawa ilmu yang sahih. Ia berkata kepada pemilik argumen tadi, “Kepastianmu bahwa penalaranmu telah memperkenankanmu untuk memahami maksud Penjelas dengan apa yang Dia bicarakan dengan jelas adalah ketidak tahuan dan ketiadaan ilmu yang sahih. Sekalipun itu kebetulan sesuai dengan ilmu, iman akan hilang darimu, sedangkan kebahagiaan terkait dengan iman dan ilmu yang sahih yang didasarkan pada doktrin.
Ilmu yang sahih adalah ilmu yang senantiasa didasarkan pada iman.”19
Para rasul dan pemberitahuan ilahi membawa apa yang dianggap mustahil oleh akal. Karena itu, akal terpaksa melakukan takwil terhadap sebagiannya agar menerimanya, dan terpaksa tunduk dan mengakui ketidak berdayaannya dalam urusan-urusan lain yang tidak menerima takwil pada asalnya. Akhirnya seseorang harus mengatakan, “Ini mempunyai aspek yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah dan tidak dapat dicapai oleh akal kita.” Semua ini adalah untuk membuat jiwa tenang – ini bukan ilmu – agar semua ini tidak menolak apa yang dibawa oleh kenabian. Ini adalah keadaan orang mukmin yang cerdas, sedangkan yang bukan mukmin tidak menerima sesuatu pun dari itu.20
Telah diwahyukan berita yang diangap mustahil oleh akal, sebagian berkenaan dengan Sisi Tertinggi, dan sebagian lain berkenaan dengan realitas-realitas dan perubahan entitas-entitas. Adapun yang berkenaan dengan Sisi Tertinggi adalah segala yang wajib diimani yang mencakup apa yang disifati oleh Tuhan tentang diri-Nya dalam Kitab-Nya dan pada lisan para rasul-Nya dan makna lahir yang tidak dapat diterima oleh akal atas dasar argumennya, kecuali dengan cara menakwilkannya dengan suatu takwil yang jauh. Maka imannya adalah iman kepada takwilnya, bukan kepada berita [yang diwahyukan] itu.21
Di mata Ibn ‘Arabi, orang yang menakwilkan berita-berita yang diwahyukan pada hakikatnya telah beriman kepada takwilnya sendiri yang dihasilkan oleh penalaran dan pemikiran dengan akalnya, bukan kepada berita-berita itu. Maka imannya telah melenceng jauh; imannya telah salah arah. Ia telah menjadi hamba takwil, hamba penalaran, hamba pemikiran, hamba akal, bukan lagi hamba Tuhan.
Sufi besar ini melancarkan kritik keras dan tajam kepada para ulama yang menakwilkan syariat untuk menarik hati para penguasa dan dengan demikian mereka mencapai kedudukan yang tinggi. Ia mengecam para ulama duniawi yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Ia berkata :
Ketika hawa nafsu menguasai jiwa dan para ulama mencari kedudukan [yang tinggi] di sisi para raja, mereka meninggalkan jalan terang dan cenderung kepada takwil yang jauh. Mereka melakukan hal itu agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan pribadi para raja dengan jalan yang dikuasai hawa nafsu mereka agar para raja bersandar dalam hal itu pada perintah syariat. Boleh jadi keadaan seorang fakih tidak mempercayai [takwil] itu, tetapi ia memberikan fatwa sesuai dengannya. Kami telah melihat sekelompok para kadi dan para fakih yang seperti itu.22 Anda harus mengetahui bahwa Allah telah memberi setan kekuatan dari kehadiran imaginasi dan memberinya kekuasaan dalam kehadiran imaginasi itu. Karena itu, ketika setan melihat seorang fakih cenderung kepada hawa nafsu yang merusaknya di sisi Allah, setan itu akan menghiasinya dengan perbuatan jahatnya dengan cara takwil aneh
yang menyediakan baginya suatu aspek yang baik dalam pertimbangan rasionalnya.23
Kerasnya dan tajamnya kritik Ibn ‘Arabi terhadap takwil ayat-ayat al-Qur’an dan para ulama yang melakukan takwil itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa Syekh ini menolak takwil. Ia mengkritik dan menolak takwil yang dikendalikan oleh penalaran, pemikiran, refleksi, apalagi yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ia mengkritik dan menolak takwil yang melenceng – apalagi yang jauh – dari apa yang dimaksud oleh Allah dengan kata-kata-Nya yang dikandung oleh Kitab-Nya. Ilmu-ilmu para
ulama yang diperoleh melalui takwil seperti ini, sebagaimana dikatakan di atas, disebut ilmu-ilmu “perolehan.” Sebaliknya, Ibn ‘Arabi menerima takwil yang diberi dan dibimbing oleh Allah. Takwil dalam arti ini, yang menurut Sufi besar ini adalah benar, diterima oleh orang-orang yang diberi keberhasilan oleh Allah dalam memahami apa yang Dia maksud dengan kata-kata yang dikandung oleh Kitab-Nya. Orang-orang seperti itu diberi oleh Allah ilmu yang tidak tercampur atau ilmu yang murni (al-‘ilm ghayr masyūb). Mereka disebut “orang-orang yang berakar kukuh dalam ilmu” (al-rāsikhūna fī al-‘ilm). Mereka tidak menggunakan penalaran, pemikiran, atau refl eksi, karena penalaran, pemikiran, atau refl eki tidak terlepas dari
kesalahan. Ilmu-ilmu yang mereka miliki dengan takwil seperti ini disebut ilmu-ilmu “pemberian.” Jenis ilmu-ilmu ini adalah hasil takwa, sebagaimana Allah berfi rman, “Bertakwalah kepada Allah, dan Dia akan mengajarimu” (Q 2:282). “Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan bagimu pembedaan (furqān)” (Q 8:29). “Yang maha Pengasih mengajarkan al-Qur’an” (Q 55:1-2).
Tampaknya bagi Ibn ‘Arabi takwil tidak boleh menyangkal dan menghapuskan makna harfi ah teks. Baginya penyingkapan makna esoterik teks, yaitu takwil, tidak boleh mengubah, apalagi menyangkal, perintah- perintah dan larangan-larangan syariat. Ia menegaskan bahwa tasawuf harus berpegang pada syariat, karena syariat adalah timbangan (mīzān) dan pemimpin (imām) yang harus diikuti dan ditaati oleh siapa pun yang menginginkan keberharhasilan dalam tasawuf.
Simaklah wasiat Ibn ‘Arabi untuk membaca dan merenungkan al- Qur’an sebagai berikut :
Hendaklah engkau membaca al-Qur’an dan merenungkannya. Ketika engkau membacanya, perhatikanlah kualitas-kualitas dan sifat-sifat terpuji yang Allah sifatkan kepada hamba-hamba-Nya yang Dia cintai. Hendaklah juga engkau bersifat dengan kualitas-kualitas dan sifat sifat itu. Perhatikan pula kualitas-kualitas dan sifat-sifat yang dicela oleh Allah dalam al-Qur’an yang dimiliki oleh orang yang Dia benci.
Maka jauhilah kualitas-kualitas dan sifat-sifat itu. Allah tidak menyebut untuk engkau kualitas-kualitas dan sifat-sifat itu dalam Kitab-Nya dan menurunkannya kecuali agar engkau mengamalkan dengan [cara] itu. Bila engkau membaca al-Qur’an, jadilah engkau al-Qur’an demi apa yang ada dalam al-Qur’an.24
Pada kutipan ini kita melihat bahwa Ibn ‘Arabi tidak hanya menganjurkan kita untuk membaca (tilāwah) tetapi juga merenungkan (tadabbur) al- Qur’an. Merenungkan (tadabbur) di sini adalah mempelajari, mengkaji dan melihat secara mendalam dengan kalbu, yang berimplikasi pada transformasi spritual dalam perjalanan menuju Allah. Membaca dan merenungkan al- Qur’an membawa seseorang kepada pengetahuan dan kesadaran tentang kualitas-kualitas dan sifat-sifat terpuji yang harus dia miliki dan kualitas kualitas dan sifat-sifat tercela yang harus dia jauhi. Kualitas-kualitas dan sifat-sifat terpuji itu adalah kualitas-kualitas dan sifat-sifat Allah, yang tidak lain adalah identik dengan al-Qur’an. Karena itu, Ibn ‘Arabi memberikan
wasiat agar kita menjadi al-Qur’an, atau berakhlak dengan al-Qur’an sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad.
Perhatikan pula wasiat Syekh ini bahwa zikir (al-dzikr) adalah al- Qur’an dan karena itu al-Qur’an adalah zikir yang paling agung. Allah berfi rman, “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan zikir” (Q 15:9), yakni al-Qur’an. Allah [melalui hadis qudsi] berkata pula, “Aku adalahteman duduk orang yang berzikir kepada-Ku.” Nabi Muhammad berkata, “Orang-orang al-Qur’an (ahl al-qur’ān) adalah orang-orang Allah (ahlu- Llāh) dan [orang-orang] istimewa-Nya. Orang-orang istimewa Sang Raja itu [Tuhan] adalah teman-teman duduk-Nya dalam sebagian besar keadaan mereka. Allah memiliki akhlak, dan akhlak itu adalah nama-nama indah ilahiah. Barang siapa yang menjadikan Tuhan (al-Haqq), maka Tuhan adalah teman intimnya. Tentu saja ia akan mendapatkan akhlak mulia sesuai dengan ukuran lama pertemanannya. Barang siapa yang berteman dengan kaum yang berzikir kepada Allah, maka Allah memasukkannya bersama mereka dalam rahmat-Nya.25
Wasiat lain Ibn ‘Arabi adalah anjurannya agar kita berkata dengan perkataan yang paling baik (bi-ahsan al-hadīts), yang tidak lain adalah al- Qur’an. Ia mengatakan,
Hendaklah engkau berkata dengan perkataan yang paling baik, yaitu al-Qur’an. Hendaklah engkau selalu membacanya dengan perenungan dan tafakur. Muda-mudahan Allah menganugerahkan pemahaman kepada engkau tentang apa yang engkau baca. Ajarkanlah al-Qur’an, niscaya engkau akan menjadi wakil Yang Maha Pengasih (nā’ib alrahmān), karena “Yang Maha Pengasih, telah mengajarkan al-Qur’an. Dia telah menciptakan manusia. Dia telah mengajarnya penerangan
(al-bayān)” (Q 55:1-4), yaitu al-Qur’an. Allah berfi rman, “Ini adalah penerangan bagi manusia,” yaitu al-Qur’an, “petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang bertakwa” (Q 3:138). Dia telah mengetahui al- Qur’an sebelum manusia Dia ciptakan. Al-Qur’an turun hanya kepada manusia. Sebagaimana al-Qur’an telah diturunkan oleh Ruh
Amin (al-rūh al-amīn) kepada kalbu Muhammad, maka demikian pula al-Qur’an diturunkan kepada setiap kalbu pembaca ketika ia membacanya. Turunnya al-Qur’an terjadi secara secara terus-menerus. Allah mengajarkan al-Qur’an sebagaimana manusia mengajarkannya. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mengetahui al-Qur’an dan mengajarkannya.26
Contoh Takwil
Kembali kepada masalah takwil ayat-ayat al-Qur’an dalam pandangan Ibn ‘Arabi, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa takwil ayat-ayat al-Qur’an yang jumlahnya sangat banyak bertebaran dalam karya-karya Sufi termasyhur dari Andalusia ini. Salah satu contoh adalah takwil firman
Allah “Wahai orang-orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafi r yang dekat dengan kamu” (Q 9:123), sebagaimana ditemukan dalam al-Tadbīrāt al-Ilāhiyyah dan al-Futūhāt al-Makkiyyah. Ibn ‘Arabi mengatakan bahwa ungkapan “orang-orang kafir yang dekat dengan kamu (alladzīna yalūnakum min al-kuff ār)” berarti “orang kafir yang paling dekat dengan kamu (aqrab al-kuff ār ilayka).” Orang kafi r yang paling dekat dengan Anda adalah “teman (al-qarīn) dalam [diri] Anda,” yang tidak lain adalah “hawa nafsu Anda (hawāka).” Hawa nafsu Anda adalah musuh Anda yang paling besar. Karena itu, perangilah hawa nafsu Anda.27 Syekh Sufi ini mengatakan pula
bahwa hawa nafsu Anda adalah “musuh paling dekat kepada Anda yang dekat dengan Anda karena ia di dalam [diri] Anda (aqrab al-a‘dā’ ilayka alladzīna yalūna-ka fa-innahu bayna janbayka)” Tidak ada yang lebih kafir di sisi Anda daripada diri Anda sendiri karena pada setiap orang ada diri yang kafi r atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Maka Ibn ‘Arabi berwasiat, “Diwajibkan bagi Anda melakukan Jihad terbesar (al-jihād alakbar), yaitu jihad Anda melawan hawa nafsu Anda, karena ia adalah musuh terbesar Anda (akbar a‘dā’i-ka).”28
Sufi terbesar dari Andalusia ini menasehatkan agar Anda berteman dengan orang-orang yang beriman, berbuat ihsan, adil dan patuh pada hukum Allah. Pada hakikatnya, iman, ihsan, keadilan, dan kepatuhan adalah teman-teman yang baik. Karena itu, berakhlak dengan sifat-sifat itu adalah jalan keselamatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Maka beliau mengingatkan agar Anda berhati-hati terhadap teman-teman yang jahat karena mereka berbahaya bagi diri Anda. Mereka itu mungkin menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Anda dan kehancuran negeri wujud Anda. Teman yang jahat itu tidak jauh dari diri Anda. Ia ada di dalam diri Anda
sendiri. “Teman (al-qarīn) dalam [diri] Anda itu adalah hawa nafsu Anda (hawāka).” Dikatakan, “Perangilah hawa nafsu Anda (jāhid hawāka), karena ia adalah musuh Anda yang paling besar.” Allah berfi rman, “Wahai orangorang beriman! Perangilah orang-orang kafi r yang dekat dengan kamu” (Q 9:123). Orang kafi r itu adalah “orang kafir yang paling dekat dengan kamu (aqrab al-kuff ār ilayka).”29
Peringatan Ibn ’Arabi ini tampaknya diinspirasi oleh perkataan Nabi Muhammad sepulang dari Perang Badar. Beliau berkata: “Kita telah kembali dari jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar.” Lalu para sahabat bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, apa jihad yang lebih besar itu?” Rasulullah menjawab: “Jihād nafs” (“Jihad melawan diri sendiri”). Pada sebagian nash (teks), ungkapan yang digunakan adalah “mujāhadat alnafs” (yang juga berarti “melawan diri”). Di dalam beberapa kitab tasawuf, ungkapan yang digunakan bukan “jihād al-nafs,” tetapi adalah “mukhālafat
al-nafs” (yang juga dapat diterjemahkan dengan “melawan atau menentang diri”). Kata nafs berarti jiwa, diri, ego, atau hawa nafsu.
Menurut Ibn ‘Arabi, dengan takwilnya, ungkapan “orang-orang kafi r yang dekat dengan kamu” (Q 9:123) bukan berarti orang-orang kafi r dari dari Bani Qurayzhah, Nadlir, Fadak, dan Khaybar. Bagi Syekh ini, mereka adalah nafs, jiwa, diri, ego, atau hawa nafsu, yang ada dalam diri setiap manusia. Takwil ini serupa dengan takwil Abu ‘Abd al-Rahman al-Sulami (w. 1021), seorang Sufi dari Persia, yang mengambil takwil Sahl al-Tustari (w. 896), seorang Sufi dari Iraq, bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang kafir yang dekat dengan kamu” (Q 9:123) adalah nafs. Sahal berkata, “Diri (alnafs) adalah kafir, maka perangilah diri dengan melawan hawa nafsunya (bi
al-mukhālafah li-hawā-hā), dan bawalah dia kepada ketaatan pada Allah dan jihad di jalan-Nya, makan apa yang halal, perkataan tentang kebenaran, dan apa yang diperintahkan untuk melawan natur (mukhālafat al-thabī‘ah).30
Cara esoterik ini dalam menangkap makna ungkapan “orang-orang kafir yang dekat dengan kamu” (Q 9:123) ini berbeda dengan cara eksoterik para ulama dalam menafsirkan ungkapan yang sama dengan arti, misalnya, orang-orang kafir “dari Bani Qurayzhah, Nadlir, Fadak, dan Khaybar,”31 atau orang-orang Arab, Romawi,32 Daylam, dan bersifat umum dalam memerangi orang-orang yang terdekat dan bahkan terjauh.33 Cara pertama melihat bahwa “orang-orang kafi r yang dekat dengan kamu” berada “di dalam diri” setiap orang beriman, sedangkan cara kedua mengartikan bahwa “orang-orang kafi r yang dekat dengan kamu” adalah orang-orang kafir yang berada “di luar diri” orang-orang beriman sebagai para pengikut Muhammad. Cara pertama lebih menekankan aspek batiniah, sedangkan cara kedua lebih menekankan aspek lahiriah. Sebuah contoh lain adalah takwil fi rman Allah, “mereka yang terusmenerus [tanpa berhenti] pada salat mereka” (Q 70:23). Apa yang dimaksud salat dalam ayat ini? Salat (al-shalāh) secara etimologis berarti “doa (aldu‘
ā’),”34 dan salat menurut syarak adalah “ibadah khusus yang waktunya ditentukan, yang sesuai dengan peraturan-peraturan dalam syariat.”35 Salat dalam arti (eksoterik) ini juga dibicarakan dengan rinci oleh Ibn ‘Arabi dalam karyanya al-Futūhāt al-Makkiyyah pada bab keenam puluh sembilan dengan judul “Fī Ma‘rifat Asrār al-Shalāh wa ‘Umūmi-hā.”36 Ia menyebutkan bahwa salat-salat fardu dan sunah muakadah (yang sangat dianjurkan) yang disyariatkan, misalnya, adalah delapan: salat lima waktu, witir malam hari, Jumat, dua hari raya, gerhana, minta hujan, istikharah, dan salat jenazah.37 Pembicaraan Syekh Terbesar ini tentang salat tidak berhenti pada aspek esoteriknya, tetapi lebih jauh pada aspek esoteriknya. Dengan kata lain, ia membicarakan salat bukan hanya dari segi syariat tetapi juga dari segi hakikat.
Tentang arti salat dalam fi rman Allah, “mereka yang terus-menerus [tanpa berhenti] pada salat mereka” (Q 70: 23), Ibn ‘Arabi mengatakan bahwa kata “al-shalāh” dalam ayat ini bukan berarti salat dalam arti syariat, tetapi salat dalam arti hakikat. Ibn ‘Arabi mengatakan,
Allah ta‘ālā berfirman, “mereka yang terus-menerus [tanpa berhenti] pada salat mereka” (Q 70: 23). Orang yang melakukan salat (al-mushallī) bermunajah dengan Rabb-nya, dan munajah (percakapan intim dan rahasia) adalah zikir. Dia (Rabb-nya) adalah teman duduk (jalīs) orang yang ingat (zikir) pada-Nya. Keadaan terus-menerus tanpa berhenti (al-dawām) pada munajah-Nya adalah bahwa sang hamba dalam semua keadaan dan perbuatannya bersama dengan Allah sebagaimana
ia dalam salatnya bermunajah dengan-Nya dalam setiap nafas…Maka bermunajatlah dengan-Nya hamba yang telah mengetahui kehadiran Tuhan bersama dengannya dalam keadaannya. Itulah keadaan terus menerus tanpa berhenti pada salat. ‘Aisyah berkata untuk mengabarkan keadaan Rasul Allah, “bahwa ia [Rasul Allah] mengingat (zikir pada) Allah pada setiap waktu” mengisyaratkan apa yang kami katakan … Ia
[Rasul Allah] dalam seluruh waktu adalah orang yang berzikir (dzākir), dan inilah yang dikatakan tentangnya, zikir kalbu (dzikr al-qalb) yang keluar dari zikir lafaz dan zikir khayal. Barang siapa berzikir pada Allah dengan zikir ini tentu Dia adalah teman duduknya terus-menerus tanpa berhenti.38
Pada kutipan kita memahami bahwa mengingat Allah dalam setiap waktu, zikir pada Allah dalam setiap saat, merasakan kehadiran Allah dalam setiap dalam setiap keadaan dan perbuatan, adalah salat dalam arti hakikat atau dalam arti esoterik. “Barang siapa yang melihat roh salat, yaitu kehadiran bersama dengan Allah dan bermunajah dengan-Nya terus menerus tanpa berhenti, maka semua perbuatannya adalah salat.” Orang orang seperti ini adalah “orang-orang yang hadir bersama dengan Allah terus-menerus tanpa berhenti (ahl al-hudlūr ma‘a Allāh ‘alā al-dawām),
yang diisyaratkan dengan firman Allah, “mereka yang terus-menerus [tanpa berhenti] pada salat mereka” (Q 70:23).39 Salat dalam arti hakikat (esoterik) ini tidak menafi kan salat dalam arti syariat (eksoterik), karena salat dalam arti syariat adalah jalan untuk mencapai salat dalam arti hakikat. Salat dalam arti syariat, meskipun memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, yang tidak mencapat tingkat salat dalam arti hakikat, adalah ibarat badan tanpa roh. Salat seperti itu tidak lebih dari perbuatan rutin, yang tidak berfungsi menghadirkan Allah dalam kalbu orang yang mengerjakan salat. Itulah salat tanpa zikir.
Kesimpulan
Mengakhiri pembicaraan ini, perlu bagi kita membuat kesimpulan tentang pandangan Ibn ‘Arabi tentang takwil al-Qur’an. Sufi besar ini menerima takwil yang dibimbing oleh Allah melalui penyingkapan intuitif (kasyf). Takwil seperti ini diterima oleh orang-orang yang diberi keberhasilan oleh Allah dalam memahami apa yang Dia maksud dengan kata-kata yang dikandung oleh Kitab-Nya. Orang-orang seperti itu diberi oleh Allah ilmu yang tidak tercampur atau ilmu yang murni (al-‘ilm ghayr masyūb). Mereka disebut “orang-orang yang berakar kukuh dalam ilmu” (al-rāsikhūna fī al-‘ilm. Ilmu-ilmu yang mereka miliki dengan takwil seperti ini disebut
ilmu-ilmu “pemberian.” Jenis ilmu-ilmu ini adalah hasil takwa, sebagaimana Allah berfirman, “Bertakwalah kepada Allah, dan Dia akan mengajarimu” (Q 2:282). “Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan bagimu pembedaan (furqān)” (Q 8:29). “Yang Maha Pengasih mengajarkan al-Qur’an” (Q 55:1-2). Karena itu, Syekh ini melancarkan kritik tajam terhadap takwil yang dikendalikan oleh penalaran, pemikiran, refleksi dan hawa nafsu karena takwil jenis ini melenceng dari apa yang dimaksud oleh Allah dengan kata-kata-Nya yang dikadung oleh Kitab-Nya.
Takwil yang didukung oleh Ibn ‘Arabi ini tetap memelihara kesesuaian antara arti lahiriah dan arti batiniah. Tidak diperkenankan adanya pertentangan antara keduanya. Arti batiniah tidak menghilangkan arti lahiriah. Takwil seperti ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap ayat al-Qur’an mengandung makna lahir dan makna batin sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad, “Dalam setiap ayat ada makna lahir dan ada makna batin.” Makna batin sama sekali tidak menghilangkan makna lahir. Takwil ini tetap menjaga kesatuan antara syariat dan hakikat, antara aspek esksoterik dan aspek esoterik.
Takwil yang diterima oleh Sufi termasyhur dari Andalusia ini bersandar pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Bagi Sufi ini tasawuf dan al-Quran tidak bisa dipisahkan karena tasawuf itu sendiri adalah berakhlak dengan akhlak Allah, yang identik dengan berakhlak dengan al-Qur’an, seperti dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Siti ‘Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad, ia menjawab, “Akhlaknya adalah al-Qur’an.” Al-Qur’an dalam arti ini adalah akhlak Allah, nama-nama Allah atau sifat-sifat-Nya.
2 William C. Chittick, h e Sufi Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination (Albany: State University of New York Press, 1989), h. xvi.
3 Chittick, h e Sufi Path of Knowledge, h. 199.
4 Nashr Hamid Abu Zayd, Falsafat al-Ta’wīl: Dirāsah fī Ta’wīl al-Qur’ān ‘inda Muhyi al-Dīn Ibn ‘Arabi (Beirut: Dar al-Tanwir dan dar al-Wahdah, 1983).
5 ‘Athif al-‘Iraqi, Nahwa Mu‘jam li’l-Falsafah al-‘Arabiyyah: Mushthalahāt wa Syakhshiyyāt (Iskandariah: Dar al-Wafa’ li-Dunya al-h abi‘ah wa al-Nasyr, 2001), h. 29, sebagaimana dikutip oleh Zaki Salim, al-Ittijāh al-Naqdī ‘inda Ibn ‘Arabī (Kairo: Maktabat al-Tsaqafah al-Diniyyah, 2005/1426), h. 93.
6 Henry Corbin, History of Islamic Philosophy, translated by Liadain Sherrard with the assistance of Philip Sherrard (London & New York: Kegan Paul International in association with Islamic Publications for the Institute of Ismaili Studies, 1993 [First published in French as Histoire de la Philosophie Islamique in 1964]), h. 12.
7 Corbin, History of Islamic Philosophy, h. 12.
8 ‘Athif al-‘Iraqi, Nahwa Mu‘jam, h. 29.
9 Ibn Rusyd, Fashl al-Maqāl fī-mā bayn al-Hikmah wa al-Syarī‘ah min al-Ittishāl, dieditoleh Muhammad ‘Imarah (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1983), h. 32, sebagaimana dikutip oleh Zaki Salim, al-Ittijāh, h. 92.
10 ‘Abu al-‘Ala ‘Afi fi , “Ibn ‘Arabī fī Dirāsatī,” dalam al-Kitāb al-Tidzkārīi al-Dzikrā al-Mi’awiyyah al-Tsāminah li-Mīlād Ibn ‘Arabī (Kairo: al-Muassasah al-Mishriyyah al-‘Ammah li’l-Ta’lif wa al-Nasyr, 1969), h. 8, sebagaimana dikutip oleh Zaki Salim, al-Ittijā al-Naqdī, h. 92.
11 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 14 volume, diedit oleh ‘Utsman Yahya (Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Ammah li’l-Kitab, 1985-1992), 13: 485, sebagaimana dikutip oleh Zaki Salim, al-Ittijā al-Naqdī, h. 92. Dalam catatan kaki selanjutnya karya ini disebut dengan singkat al-Futūhāt 14V.
12 Zaki Salim, al-Ittijā al-Naqdī, h. 92.
13 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 14V, 13: 161.
14 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 14V, 3: 282.
15 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 9 volume [volume 9 khusus untuk indeks], diedit oleh Ahmad Syams al-Din (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 6: 354, 359; 8: 350. Dalam catatan kaki selanjutnya karya ini disebut dengan singkat al-Futūhāt 9V.
16 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 3: 431.
17 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 6: 306.
18 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 4: 175, 335-36.
19 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 4: 432.
20 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 1: 331.
21 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 1: 331.
22 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 5: 101.
23 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 5: 102.
24 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 8: 257.
25 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 8: 258.
26 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 8:286.
27 Ibn ‘Arabi, al-Tadbīrāt al-Ilāhiyyah fī Ishlāh al-Mamlakah al-Insāniyyah, dalam H.S. Nyberg, Kleinere Schriften des Ibn al-‘Arabi (Leiden: Brill, 1919), h.150-51.
28 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, h. 8: 260.
29 Ibn ‘Arabi, Al-Tadbīrāt al-Ilāhiyyah, h. 150-51.
30 Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad ibn al-Husayn ibn Musa al-Azadi al-Sulami, Haqa’iq al-Tafsir: Tafsir al-Qur’an al-‘Aziz, Juz Pertama (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2001/1421), h. 292. Di sini perlu ada catatan tentang arti “thabī‘ah” (natur). Dalam sebuah catatan kaki, William C. Chittick menulis, “Natur” (thabī‘ah) adalah materia tak terlihat yang membolehkan segala sesuatu di bawah alam roh-roh (‘ālam al-arwāh) menjadi zahir, yaitu segala sesuatu di dalam alam khayal dan alam jasad. Dalam arti ini, ia membuat “jasad” sebagai lawan bagi roh sesuatu; atau, ia adalah “kegelapan” sesuatu sebagai lawan bagi “cahaya”-nya. Natur terdiri dari empat kecenderungan dasar, yang dikenal sebagai “natur-natur” (thabā’i‘): panas, dingin, basah, dan kering. Dalam arti kedua, Natur adalah sinonim dengan Nafas Sang Maha Pengasih [nafas al-rahmān] (Chittick, h e Sufi Path of Knowledge, h. 391, catatan kaki no. 25). “Kegelapan ‘Natur’ (thabī‘ah), harus diingat, dikontraskan dengan cahaya roh, yang dengannya daya berpikir berhubungan dekat” (Chittick, h e Sufi Path, h. 407, catatan kaki no. 17).
31 Abu h ahir ibn Ya‘kub al-Fayruzabadi, Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr ibn ‘Abbās (Beirut: Dar al-Fikr, 2001/1421), h. 207.
32 Tentang orang-orang Romawi, dikatakan bahwa mereka adalah “orang-orang kafir yang dekat dengan kamu” karena “mereka adalah penduduk Syam (sekarang Suriah) dan Syam lebih dekat dengan Madinah daripada Iraq” (Abu Muhammad al-Husayn ib Mas‘ud al-Farra’ al-Baghawi, Ma‘ālim al-Tanzīl fī al-Tafsī wa al-Ta’wīl, 5 volume [Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M/ 1422 H], 3: 78).
33 Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashri, al-Nukat wa al- ‘Uyūn: Tafsīr al-Mawardī, 6 volume (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah & Mu’assasat al-Kutub al-Tsaqafi yyah, t.th), 2: 415-16; Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud ibn ‘Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi, al-Kasysyāf ‘an Haqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl, 4 volume (Beirut: Dar al-Fikr, 2006 M/ 1426-1427 H), 2: 222; ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam al-Sulami, Tafsīr al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam, 2 volume (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 1: 268; Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jāmi‘ li-Ahkām al-Qur’ān, 10 volume (Kairo: Dar al-Hadits, 2002 M/ 1423 H), 4:607.
34 Al-Mu‘jam al-‘Arabī al-Asāsī li’l-Nāthiqīna bi’l-‘Arabiyyah wa Muta‘allimī-hā, disusun dan dipersiapkan oleh Jama‘ah min Kibar al-Lughawiyyin al-‘Arab dengan biaya dari al-Manthiqah al-‘Arabiyyah li’l-Tarbiyyah wa al-Tsaqafah wa al-‘Ulum (Beirut: Larose, t.th), h. 746.
35 Al-Mu‘jam al-‘Arabī, h. 746.
36 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 2: 14-248.
37 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 2: 16.
38 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 5: 330.
39 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt 9V, 2: 14.
Daftar Rujukan
- Abu Zayd, Nashr Hamid. Falsafat al-Ta’wīl: Dirāsah fī Ta’wīl al-Qur’ān ‘inda Muhyi al-Dīn Ibn ‘Arabī. Beirut: Dar al-Tanwir dan Dar al-Wahdah, 1983.
- ‘Afi fi , Abu al-‘Ala. “Ibn ‘Arabī fī Dirāsatī.” Dalam al-Kitāb al-Tidzkārī al-Dzikrā al-Mi’awiyyah al-Tsāminah li-Mīlād Ibn ‘Arabī. Kairo: al-Mu’assasah al- Mishriyyah al-‘Ammah li’l-Ta’lif wa al-Nasyr, 1969.
- Baghawi, Abu Muhammad al-Husayn ib Mas‘ud al-Farra’ al-. Ma‘ālim al-Tanzīl fī al-Tafsī wa al-Ta’wīl. 5 volume. Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M/ 1422 H.
- Chittick, William C. h e Sufi Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination. Albany, NY: State University of New York Press, 1989.
- Corbin, Henry. History of Islamic Philosophy. Translated by Liadain Sherrard with the assistance of Philip Sherrard. London & New York: Kegan Paul International in association with Islamic Publications for the Institute of Ismaili Studies, 1993 [First published in French as Histoire de la Philosophie Islamique in 1964].
- Fayruzabadi, Abu h ahir ibn Ya‘kub al-. Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr ibn ‘Abbās. Beirut: Dar al-Fikr, 2001/1421.
- Ibn ‘Arabi. Al-Futūhāt al-Makkiyyah. 14 volume. Diedit oleh ‘Utsman Yahya. Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Ammah li’l-Kitab, 1985-1992.
- Ibn ‘Arabi. Al-Futūhāt al-Makkiyyah. 9 volume [volume 9 khusus untuk indeks]. Diedit oleh Ahmad Syams al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Ibn ‘Arabi. Al-Tadbīrāt al-Ilāhiyyah fī Ishlāh al-Mamlakah al-Insāniyyah. Dalam H.S. Nyberg, Kleinere Schriften des Ibn al-‘Arabi. Leiden: Brill, 1919).
- Ibn Rusyd. Fashl al-Maqāl fī-mā bayn al-Hikmah wa al-Syarī‘ah min al-Ittishāl. Diedit oleh Muhammad ‘Imarah. Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1983.
- ‘Iraqi, ‘Athif al-. Nahwa Mu‘jam li’l-Falsafah al-‘Arabiyyah: Mushthalahāt wa Syakhshiyyāt. Iskandariah: Dar al-Wafa’ li-Dunya al-h abi‘ah wa al-Nasyr, 2001.
- Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-. Al-Nukat wa al-‘Uyūn:
- Tafsīr al-Mawardī. 6 volume. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah & Mu’assasat al-Kutub al-Tsaqafi yyah, t.th.
- Noer, Kautsar Azhari. “Al-Qur’an dan Tasawuf.” Bayan, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam 1/1 (2011): 93-114.
- Noer, Kautsar Azhari. “Pemerintahan Ilahi atas Kerajaan Manusia: Psikologi Ibn ‘Arabi tentang Roh.” Kanz Philosophia, A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies 1/ 2 (Augustust – December 2011): 199-214.
- Qurthubi, Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-. Al-Jāmi‘ li- Ahkām al-Qur’ān. 10 volume. Kairo: Dar al-Hadits, 2002 M/ 1423 H.
- Salim, Zaki. Al-Ittijāh al-Naqdī ‘inda Ibn ‘Arabī. Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyyah, 2005/1426.
- Sulami, ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam al-. Tafsīr al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam. 2 volume. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Sulami, Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad ibn al-Husayn ibn Musa al-Azadi al-. Haqa’iq al-Tafsir: Tafsir al-Qur’an al-‘Aziz. Juz Pertama. Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2001/1421.
- Zamakhsyari, Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud ibn ‘Umar al-. Al-Kasysyāf ‘an Haqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl. 4 volume. Beirut: Dar al-Fikr, 2006 M/ 1426-1427 H.